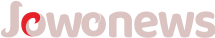Oleh : Hamam Fitriana
Kasus pelajar meminta dispensasi nikah karena hamil duluan di kabupaten Ponorogo menjadi trending topic berita nasional. Status pelajar yang masih melekat pada diri anak tentunya menjadi episentrum keprihatinan dunia pendidikan. Bagaimana tidak, pelajar yang seharusnya memiliki seperangkat bekal untuk merestriksi diri dari tindakan di luar batas justru kebablasan ihwal seksualitas.
Fenomena ini tentu mencoreng dunia pendidikan yang dirasa gagal dalam mendidik para pelajar ihwal seksualitas. Narasi seksualitas sudah lama diperbincangkan di ruang publik oleh pelbagai lembaga feminisme, perempuan, anak-anak, HAM, dan pendidikan. Akan tetapi narasi seksualitas di ranah pendidikan nampaknya masih sunyi untuk diedukasikan kepada pelajar.
Minimnya edukasi akan seksualitas di tingkat pendidikan dasar (SD, SMP, SMA) berkorelasi dengan banyaknya pelajar yang krisis edukasi seksual. Data pada Pengadilan Agama (PA) Ponorogo menerima 191 permohonan anak untuk menikah dini selama 2022 dengan rincian 115 perkara hamil di luar nikah menjadi fakta bahwa ada disparitas edukasi seksual di ranah pendidikan atau bahkan dapat dikatakan sebagai kecelakaan faktual pendidikan.
Pengajuan dispensasi yang dilakukan oleh 7 siswa SMP karena hamil duluan menjadi preseden buruk yang perlu direnungkan oleh semua pihak pemangku kekuasaan tak terkecuali pendidikan. Pemangku pendidikan perlu responsif dan membuat kebijakan yang dapat mengedukasi pelajar ihwal seksualitas. Perlu adanya regulasi dan edukasi seksual yang masif dilakukan di ranah pendidikan dasar.
Di era digital, seksualitas tidak dapat dihindarkan dari dunia pelajar. Kemudahan dan kecepatan dunia informasi membuat pelajar dapat berselancar untuk mengakses berbagai hal termasuk yang tabu untuk dilihat seperti ponografi dan kekerasan. Pendidikan perlu merespon dengan memberikan edukasi seksual sedini mungkin. Artinya pendidikan sudah mulai bergerak memberikan edukasi pada pelajar di tataran sekolah dasar. Bahkan orang tua perlu diberikan edukasi seksual sejak sebelum memiliki anak. Harapannya agar setelah mempunyai anak, orang tua dapat mengedukasi seksual pada anak-anaknya dengan tepat.
Problem liyan yang masih meresidu justru ada pada guru sebagai pendidik. Adanya stereotip seksualitas tabu untuk dibicarakan apalagi diajarkan masih menghantui guru untuk mengajarkannya pada pelajar. Historitas budaya patriarki yang mewarnai hidup berbangsa dan bernegara ikut berkontribusi akan kegagapan bertindak. Kegagapan ini tentu perlu direspon dengan membuka pikiran (open mind) dan menjadi agen guru progresif. Sehingga kegagapan untuk menerangkan edukasi seksual dapat dieliminasi.
Guru membekali diri dengan pemahaman secara utuh akan edukasi seksual dan pemerintah memfasilitasi semua guru dan calon guru untuk belajar edukasi seksual. Selain itu, perlu adanya kejelasan regulasi yang kemudian diturunkan ke tingkatan kurikulum sebagai wadah edukasi seksual pada semua jenjang pendidikan. Pada level kurikulum inilah nantinya edukasi seksual diimplementasikan di mata pelajaran. Pada dasarnya, salah satu orientasi dari pembekalan edukasi seksual tidak lain untuk mencegah 3 dosa besar pendidikan yakni perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi.
Edukasi seksual pada ranah pendidikan formal tidak akan berjalan efektif tanpa adanya kerja kolektif semua pihak. Pihak sekolah selaku kepanjangan tangan pemerintah dalam ranah pendidikan, perlu merangkul orang tua anak, pemangku agama, pemangku adat, tokoh masyarakat, serta para pengiat anak dan liyan. Kerja kolektif tersebut merupakan manifestasi identitas masyarakat Indonesia yang dikenal dengan semboyan gotong-royong.